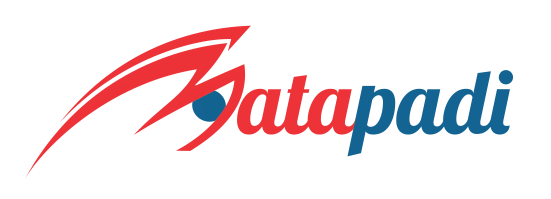NASIONALISME TANPA AMNESIA
April 12, 2023
MAYOR KAWILARANG DAN HARTA KARUN JEPANG
June 5, 2023Begitu gagal membentuk “republik kerakyatan” di Madiun pada 19 September 1948, FDR (front yang digagas oleh PKI), amburadul. Tidak saja para pengikutnya banyak ditumpas pasukan pemerintah Sukarno-Hatta, juga para tokohnya banyak yang terbunuh dan tertangkap. Muso dan Amir Sjarifoedin adalah dua di antaranya.
Pati yang merupakan wilayah FDR terkuat kedua setelah Madiun, tak luput dari aksi pembersihan yang dilakukan oleh gabungan Divisi Siliwangi dan Divisi Ronggolawe. Setelah menjalani perannya sebagai residen Pati vesi FDR selama tiga puluh hari, Dokter Wiroreno akhirnya berhasil ditangkap di rumah kediamannya.
“Di Pati, pimpinan FDR setempat, Wiroreno, dibereskan…” ungkap Harry A. Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak.
Menurut Soe Hok Gie dalam Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Wiroreno sejatinya adalah seorang dokter idealis yang memiliki sikap humanis. Bisa jadi itu disebabkan latar belakang dia yang dibesarkan dalam kepahitan era Hindia Belanda. Pada waktu kuliah, Wiroreno harus berhenti dua tahun untuk mencari uang terlebih dahulu. Setelah lulus, dia bekerja sebagai dokter pemerintah dan ditempatkan di mana-mana.
Di awal karirnya sebagai dokter, dia banyak bersinggungan dengan para pamong praja dan bupati-bupati yang kerjannya hanya memeras rakyat. Karena sikap itu pula, keberpihakan Wiroreno kepada wong cilik semakin kuat selama zaman Jepang karena sebagai dokter, dia banyak berhadapan langsung dengan rakyat yang kelaparan.
Sikapnya terhadap politik juga apatis. Baginya, politisi merupakan badut-badut sekaligus tukang sulap yang selalu menang. Blokade Belanda, kemelaratan, dan sulitnya obat-obatan membuatnya menjadi seorang “populis”.
“Dia tidak ke Yogya karena baginya Yogya merupakan sarang “dekadensi” cita- cita revolusi,” ungkap Soe Hok Gie.
Wiroreno memutuskan untuk tinggal di Kudus, sebuah kota dekat garis demarkasi. Di sana dia sering mengobati banyak prajurit yang terluka. Sebagai ahli bedah yang brilian, dr. Wiroreno bekerja di tengah-tengah rakyat dan hidup menderita bersama-sama rakyat. Dalam sikap puritan ini, dia mendapatkan dirinya menyatu terhadap revolusi. Akan tetapi, tragedi lain tidak disadarinya karena perlahan-lahan dia ditelan oleh ideologi komunis tanpa dirinya sadar telah menjadi seorang komunis.
Menurut Soebadio Sastrosatomo, tokoh keluarga-keluarga komunis dari daerah pesisir seperti Mudigdo dan Abdulmadjid-lah yang dianggap bertanggungjawab menyeret seorang lurus seperti Wiroreno masuk ke dalam FDR.
Dalam pengadilan kilat yang dilakukan tentara, Wiroreno dinyatakan bersalah karena dianggap makar terhadap pemerintah yang sah. Tak ada hukuman yang pantas dilakoni pelaku kejahatan politik itu selain hukuman mati. Dengan tabah, Wiroreno menerima keputusan tersebut. Sebelum eksekusi dilakukan, dia menuliskan pesan terakhirnya kepada sang istri agar juga tabah dan menerima nasibnya.
“Hij die voor het kleine volk stridjt, moet op het schavot sterven (Siapa saja yang berjuang untuk rakyat kecil, harus mati di tiang gantungan),” ungkapnya seperti dikisahkan Boes Soewandi dalam buku Pasukan ‘T’ Ronggolawe.
Waktu hukuman mati pun tiba pada suatu hari di akhir November 1948. Tempatnya di Alun-alun Kudus. Sebagai komandan tim eksekutor, seorang kapten dari Divisi Siliwangi menugaskan Letnan Dua Boes Soewandi, anggota Pasukan T Ronggolawe yang di-BKO-kan ke Batalyon Kala Hitam Divisi Siliwangi pimpinan Mayor Kemal Idris.
Mendapat tugas itu, alih-alih menerima, Boes malah menjadi stres. Kenapa? Karena Wiroreno tak lain adalah sahabat baik ayahnya yakni Dokter Soewandi. Dia sendiri sudah terlanjur akrab dengan sang dokter yang sudah dianggap paman sendiri. Singkat cerita, Boes menolak perintah tersebut.
“Sang kapten marah dan mengancam akan me-mahmil-kan ayah saya,” ungkap Delly Soewandi, salah satu putra dari almarhum Boes Soewandi.
Sebagai gantinya Letnan Dua Ali Said (sahabat Boes) mengambil-alih peran Boes. Kendati mengenal baik juga Wiroreno, namun Ali Said (kelak menjadi jaksa agung RI ke-9) secara psikologis lebih siap melaksanakan “tugas berat” tersebut.
Di hadapan rakyat yang pernah merasakan kebaikannya, Wiroreno dengan tenang dan gagah membiarkan calon penembaknya melilitkan kain berwarna putih ke bagian wajahnya. Sebelum ikut melepaskan peluru ke tubuh sang dokter, sang komandan regu penembak terlebih dahulu meminta maaf. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tembakan membahana di Alun-alun Kudus. Tubuh Wiroreno yang dibalut pakaian serba putih mengejang lantas terkulai tepat di bawah sebuah pohon besar. Darah bersimbah memenuhi dadanya.
Kematian Dokter Wiroreno seolah menyusul nasib yang dialami sahabat baiknya (selain Dokter Soewandi) bernama Dokter Loekmonohadi tiga bulan sebelumnya. Ironisnya, jika Wiroreno tewas di ujung peluru pasukan anti PKI, maka Loekmonohadi menemui ajal justru karena dibunuh oleh para pengikut PKI. (Hendijo).