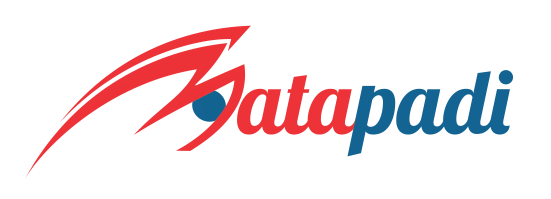Tergulingnya Truk Pembawa Bonek
May 15, 2020Ki Wasyid dan Perlawanan Para Kiai
May 20, 2020Buya Hamka, Tak Pernah Ada Dendam
“Saya tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dendam itu termasuk dosa. Selama dua tahun empat bulan saya ditahan, saya merasa itu semua merupakan anugerah yang tiada terhingga dari Allah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kitab tafsir Al Quran 30 juz. Bila bukan dalam tahanan, tidak mungkin ada waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu…”
Pada sebuah siang hari, 27 Januari 1964 atau 12 Ramadhan 1383 Hijriah, Buya Hamka baru saja beristirahat setelah memberikan pengajian mingguan. Di tengah istirahatnya, tiba-tiba Buya mendapatkan tamu beberapa orang laki-laki yang berbadan tegap.
Para tamu itu berpakaian preman, tetapi beberapa di antaranya tampak menenteng Revolver di pinggang. Mereka datang disertai dengan Surat Perintah Penahanan. Rupanya, Buya hendak dibawa oleh beberapa orang orang polisi yang berpakaian preman itu.
“Jadi saya ditangkap?” ujar Buya pelan-pelan agar tak mengejutkan istrinya yang sedang sakit. Buya sendiri masih diliputi keheranan atas kedatangan para polisi itu.
Tidak ada informasi ke mana Buya hendak dibawa. Hanya ada pesan agar pihak keluarga menghubungi Mabes Polri untuk informasi lebih lanjut.
Dibawalah Buya ke dalam sebuah mobil yang segera melesat, entah ke mana.
Dalam kondisi letih berpuasa, dan tidak tahu menahu apa kesalahannya, Buya Hamka dibawa bersama polisi yang menjemputnya. Empat hari kemudian, Buya baru tahu ada tuduhan dihadapkan kepadanya. Tuduhan disesuaikan dengan Pen Pres No. 11/1963.
“Saudara pengkhianat! Menjual negara kepada Malaysia!”, gertak salah seorang anggota polisi.
Tuduhan yang tak terkira, tuduhan sebagai pengkhianat tentulah sangat menyakitkan. Buya terguncang dan hampir terpancing emosinya. Buya hanya menangis dalam tuduhan yang tak beralasan itu.
“Janganlah saya disiksa seperti itu. Bikin sajalah satu pengakuan bagaimana baiknya, akan saya tandatangani. Tetapi kata-kata demikian janganlah saudara ulangi,” pinta Buya dalam sebuah pemeriksaan.
“Memang saudara pengkhianat!”, katanya lagi dan penyidik polisi itupun berlalu pergi.
Dalam tuduhan yang berdasar sesuai Pen Pres No. 11/1963 itu, Buya Hamka dituduh terlibat dalam rapat rahasia menggulingkan presiden; dituduh menerima uang empat juta yang tidak jelas mata uangnya dari Perdana Menteri Malaysia; memberikan kuliah yang bersifat subversif, dan berbagai tuduhan kejahatan lainnya.
Singkatnya, Buya Hamka akhirnya ditahan tanpa proses pengadilan. Dua tahun lebih Buya berada dalam tahanan yang sepi dan dingin.
Pengingat Soekarno
Pada tanggal 17 Agustus 1958, dengan gaya orasinya yang khas, Presiden Soekarno mengkritik dan mencela dengan keras berlangsungnya Muktamar Alim Ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang setahun sebelumnya. Muktamar berlangsung pada 8-11 September 1957.
Berkatalah Presiden dalam pidatonya bahwa, muktamar itu sebagai suatu gerakan komunis phobia, kontrarevolusi dan dianggap perbuatan yang amoral.
Seperti biasa, pidato Sang Pemimpin Besar Revolusi ini selalu berapi-api dan penuh agitative. Pidato yang selalu ditunggu dan disambut gemuruh massa. Yang kata, kalimat dan nada bicaranya mampu menghipnotis bagi siapapun yang mendengarnya.
Menurut Buya Hamka, lazimnya pidato-pidatonya itu akan dianggap sebagai ajaran-ajaran yang akan diterima tanpa syarat (reserve) dari sang Pemimpin Besar Revolusi.
Saat itu, banyak orang yang tidak tahu apa gerangan yang dihasilkan oleh alim-ulama yang berkonferensi di Palembang itu karena kurangnya publikasi.
Hasil keputusan dari muktamar tersebut secara eksplisit menentang eksistensi komunis. Kafir, sesat, dan haram hukumnya untuk umat Islam, demikian inti dari keputusan muktamar itu. Tentu keputusan ini bukan tanpa dalil dan tanpa sebab, apalagi pengalaman buruk pada September 1948 masih membekas.
Pada masa-masa berlakunya demokrasi liberal, boleh dikata merupakan masa-masa kemesraan antara Soekarno dengan golongan komunis. Cengkeraman komunis tampak semakin kuat. PKI tampak semakin longgar berkuasa. Pengaruhnya bahkan hingga ke Angkatan Perang.
Terjadi polarisasi dan adu domba di dalam masyarakat. Tuduhan untuk mendeskriditkan para pihak yang berseberangan dengan kekuasaan akan dengan mudah dituduh sebagai pihak yang kontra revolusi, intoleran, anti-Pancasila, atau komunis phobia.
Pun dengan kalangan di antara umat Islam sendiri terbelah. Umumnya, para petualang spiritual-religiuslah yang terjebak dalam arus ini akan cenderung mendekat dengan kekuasaan pemerintahan. Menunduk bahkan menghamba.
Hamka pernah mengkritik orang-orang dari kalangan umat Islam ini terjebak dalam indoktrinasi ini, yang akan tanpa sebab memilih tunduk tanpa reserve pada Soekarno dengan ajaran-ajaran yang penuh maksiat bermesra dengan komunis di bawah panji-panji Nasakom.
Berulang dan terus berulang. Dan bagi para tokoh alim ulama yang dipandang kontra-revolusi, yang telah memutus komunis sebagai paham kafir. Maka mereka akan menjadi sasaran sebagai pihak yang harus diperangi, jika perlu akan dihina dalam setiap pidato atau dalam setiap tulisan.
Kekuasaan Soekarno memang hampir absolut. Dampaknya, masyarakat didominasi oleh publikasi-publikasi dari pembela Soekarno dan surat-surat kabar komunis, dengan isi kebanyakan mencaci maki penyelenggaran muktamar tersebut, termasuk dengan para alim-ulama yang ada di dalamnya.
Tak cuma itu, banyak di antara mereka yang dilekatkan dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar itu umumnya akan berujung pada pemenjaraan tanpa pengadilan.
Sebut saja Kiai Haji M Isa Anshary misalnya, sebagai ketua yang menandatangani resolusi dari Mukatamar itu, pada tahun 1962, ia dipenjarakan tanpa proses pengadilan selama kurang lebih 4 tahun.
Beberapa waktu sebelum diumumkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dalam sebuah sidang di Badan Konstituante, Buya Hamka yang ketika itu masih mewakili Partai Masyumi, pernah menginterupsi Presiden Sukarno.
Saat itu, Presiden Soekarno tengah mempromosikan Kabinet Empat Kaki dengan menyebut, “Inilah shiraatal mustaqiim (jalan yang lurus)”.
Buya Hamka yang tidak setuju dengan gagasan Presiden Soekarno itu kemudian menginterupsi, “… itu bukan shiraatal mustaqiim, tapi shirat ilal jahim (jalan menuju neraka),” karena memberi kesempatan bagi komunisme untuk berkuasa.
Tak lama setelah itu, Masyumi diminta membubarkan diri karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah. Masyumi menentang ide Kabinet Empat Kaki karena dianggap memberi ruang pada komunisme melalui PKI.
Bertahan dalam Diam
Pada tanggal 5 Juli 1959, di tengah berbagai macam kemelut, dan negara tengah berada di ambang perpecahan, Presiden dengan dukungan Angkatan Darat, mengumumkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.
Bung Karno kemudian bahkan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.
Situasi ini memunculkan rasa ketidakpuasan di tengah sengkarut kondisi perekonomian negara. Belum lagi munculnya berbagai macam gerakan koreksi di daerah-daerah terhadap pemerintah pusat, seperti PRRI dan Permesta, yang beberapa di antaranya diduga melibatkan tokoh-tokoh dari PSI dan Masyumi.
Praktis keadaan ini menguntungkan posisi PKI dalam kancah politik nasional. Pengaruhnya kian kuat dalam pemerintahan. Termasuk dalam soal mempengaruhi keputusan presiden dalam mendesak pembubaran Masyumi.
Namun presiden tak cukup punya nyali. Ia hanya meminta Masyumi membubarkan diri dan beberapa tokoh yang diduga terlibat agar meminta maaf secara terbuka atas “keterlibatan” mereka dalam PRRI.
Masyumi pada akhirnya membubarkan diri. Tentu ini menjadikan rival utama politik PKI dalam pemerintahan hilang. PKI melenggang menang dalam gelanggang. Setelahnya, Angkatan Darat dalam bidikan.
Tahun 1960-an merupakan salah satu periode buruk dari bangsa Indonesia. Keadaan ekonomi mengalami inflasi besar-besaran. Situasi politik tidak menentu seiring dengan dibubarkannya Badan Konstituante hasil Pemilu dan digantikan oleh orang-orang yang oleh Presiden Sukarno tunjuk sendiri.
Di banyak daerah, PKI juga mulai menjalankan ide kesejahteraan ala mereka, dengan merebut banyak lahan dari tuan-tuan tanah. Hal ini memicu terjadinya banyak kerusuhan di daerah.
PKI kemudian berkembang sebagai kekuatan politik yang dominan, terutama di dalam kalangan pemerintahan Soekarno. Bahkan, pengaruh PKI tidak hanya mendominasi dalam bidang politik dan Angkatan Perang, tetapi propaganda mereka juga menggunakan instrumen dalam berbagai bidang.
Agitasi dan propaganda PKI juga masuk dalam dunia sastra dan budaya. Di mana Buya Hamka, sebagai seorang sastrawan, juga ada di dalamnya.
Pada tahun-tahun itu telah terjadi peristiwa yang oleh beberapa tokoh disebutnya sebagai Prahara Budaya, sebuah peristiwa ‘peperangan’ sastra dan budaya antara sastrawan yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan sastrawan yang tergabung dalam Manikebu (Manifest Kebudayaan).
Sejumlah sastrawan yang kontra PKI diserang, seperti HB Jasin, Sutan Takdir Alisjahbana, Trisno Sumardjo, Asrul Sani, Misbach Yusa Biran, Bur Rasuanto, termasuk dengan Buya Hamka. Apalagi Buya Hamka aktif di Muhammadiyah dan Masyumi yang diketahui kontra PKI, maka jelas dia dijadikan sebagai sasaran serangan.
Pada tahun 1963, Harian Rakyat yang berbau komunis menempatkan berita headline yang menyatakan bahwa Tenggelamnya Kapal Van der Vijck adalah hasil jiplakan oleh Hamka. Sedangkan Harian Bintang Timur dalam Lembaran Lentera, juga memuat dan mengulas bagaimana Hamka mencuri karangan asli dari pengarang Alvonso Care, seorang pujangga Perancis. Lembaran Lentera ini diasuh oleh Pramoedya Ananta Toer.
Sejak saat itu, berbulan-bulan lamanya kedua koran komunis itu sering membuat tulisan-tulisan yang mendiskreditkan Hamka. Tidak hanya menyerang karya sastranya, bahkan mereka juga menyerang secara pribadi, ad hominem.
Namun Hamka tetap tenang dan tidak merasa terusik dengan fitnahan dan hujatan-hujatan itu.
Lembut dan Pemaaf
Semasa Orde Lama, Buya Hamka juga termasuk tokoh yang rajin mengkritik pemerintahan Soekarno terkait dengan kedekatannya dengan PKI. Selain itu, Buya Hamka berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi Presiden Soekarno.
Maka, wajar saja kalau akhirnya dia dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang dibentuknya, Panji Masyarat, juga pernah dibredel Soekarno, hanya karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita” yang terkenal itu.
Tulisan Hatta itu memang berisi kritikan tajam terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Bung Karno. Yang kemudian terbukti dijalankan dengan otoriter.
Selama hidupnya, Buya Hamka dikenal sebagai sosok yang pemaaf dan selalu berusaha menghindari konflik, juga dikenal sosok yang tidak pernah menaruh dendam.
Hal tersebut dibuktikan Buya Hamka saat mendapat kabar tentang meninggalnya Bung Karno pada 16 Juni 1970, yang disampaikan oleh ajudan Soekarno kepada Buya.
“Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku,” demikian isi pesan Bung Karno kepada Hamka.
Permintaan itu akhirnya dipenuhi oleh Buya, sama sekali tak tersirat dendam dan kebencian dalam dirinya.
Buya Hamka hampir sama dengan Natsir, jika ia bersebrangan pendapat bukan berarti ia juga akan berjarak dengan orang-orangnya dengan membenci. Tak ada dendam dalam diri mereka. Sekalipun pada masa-masa sebelumnya banyak di antara kawan juga lawannya yang menyerang pribadi.
Tak sekalipun mendendam atas pribadi, atas personalnya. Jika berseberangan, maka itu adalah dalam ideologinya. Hal yang tak (mungkin) bisa dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. []
Oleh: @matapadi