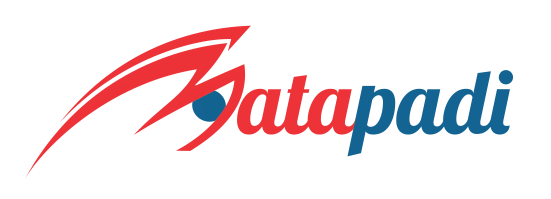Buku Sulianti Saroso: Dari Kesehatan Reproduksi Ibu Hingga Kesehatan Anak Indonesia
March 29, 2024
Rilis Buku ‘Demi Republik’, Hendi Jo Angkat Kisah Pejuang Asal Kota Bogor Harun Kabir
June 25, 2024Oleh: Martin Sitompul
Perang Kemerdekaan Indonesia bukan hanya cerita tentang komandan di medan tempur. Ia juga seyogianya tak melulu membicarakan tokoh-tokoh besar yang tercatat dalam buku sejarah. Justru yang sering terluput adalah orang-orang biasa, anak buah komandan di palagan atau pendukung para pemimpin perjuangan, yang mau mengorbankan apa yang mereka punya, bahkan nyawa sekalipun.
“Mereka berjuang tanpa memikirkan masalah apa mereka dikenang atau tidak. Tentu saja mereka jumlahnya sangat banyak, jutaan orang mungkin, yang ikut berjuang tahun 1945—1949. Dan sebagian dari mereka saya temui ketika pertama kali menjadi jurnalis tahun 1999,” tutur jurnalis sejarah Hendi Johari dalam diskusi bukunya Orang-orang di Garis Depan oleh komunitas Temu Sejarah secara daring (23/05).
Kisah Dasuki, misalnya, mantan pimpinan gerilyawan Indonesia di Sukabumi. Semasa perang, Dasuki bertempur menghadapi sepasukan tentara Sekutu yang pernah mengalahkan Jepang di Birma. Setengah abad berselang, Dasuki tua menjalani nasib sebagai penjual mainan anak-anak di sekolah SD dekat jalan Pelabuhan Ratu. Anak-anak bocah kerap mengerumuni Dasuki yang terampil membuat mainan bebek-bebekan dari kayu.
“Padahal dia dulu memimpin satu kompi pasukan yang menghancurkan prajurit-prajurit Sekutu yang menang perang di Birma. Ini cukup mengagetkan buat saya. Jadi, saya berpikir suatu hari saya harus menulis tentang dia,” ujar Hendi.
Dari sekian banyak veteran perang yang ditemuinya, menurut Hendi, hampir semua terlibat dalam pertempuran besar. Sayangnya, sejarah hanya mencatat lakon para pucuk pimpinan. Sementara itu, orang-orang bawahan yang berada di garis depan mati-matian berjuang menyabung nyawa lantas kemudian terlupakan begitu saja. Mereka hanya dikenang dengan sebutan: para pejuang.
Pejuang dalam perang memang lekat dengan lekat dengan laki-laki atau maskulinitas. Namun, buku ini juga mengangkat cerita tentang kaum perempuan. Bukan sebagai petugas palang merah atau juru masak di dapur umum, melainkan kombatan yang ikut bertempur memanggul senjata. Selain kombatan, para perempuan di medan perang juga ada berperan sebagai mata-mata, pengantar peluru, atau bahkan pengambil granat.
Soesilawati, salah satunya. Anggota Laskar Wanita (Laswi) di Bandung pada 1946 itu dengan menunggang kuda, dia menenteng satu peti berisi kepala seorang perwira muda Gurkha dari kesatuan British India Army (BIA) yang berhasil ditebasnya dalam duel satu lawan satu. Peti berisi kepala musuh itu kemudian diantarkannya ke markas Komandemen Jawa Barat. Pemandangan itu bikin Kolonel Abdul Haris Nasution, panglima komandemen, bergidik ngeri sekaligus terpukau pada keberanian perempuan pejuang di front Bandung.
Selain itu, di Bekasi juga ada kesatuan bersenjata bernama Srikandi Indonesia yang terdiri dari putri-putri petani. Mereka bertempur di bawah pimpinan Laskar Rakyat Djakarta Raya. Begitu bejibunnya perempuan yang ikut bertempur di garis depan sampai membuat Kolonel Moeffreni Moe’min, komandan Resimen Cikampek, kebingungan sekaligus prihatin. Banyak yang gugur dalam pertempuran, tapi di sisi lain, keberanian mereka melebihi laki-laki. Dari keadaan inilah kemudian komponis Ismail Marzuki menciptakan lagu “Melati di Tapal Batas”, yang mengajak para srikandi itu kembali pulang dari medan perang.
“Para perempuan itu tidak memiliki urat takut lagi,” kata Hendi Jo. “Karena situasi perjuangan saat itu, mereka juga ikut memanggul senjata dengan penuh semangat.”
Motivasi para pejuang di garis depan pun menarik disimak. Orang hari ini mungkin akan terkejut mendengar satu kompi orang-orang Kristen menginduk kepada Laskar Hizbullah yang berafiliasi Islam. Itulah kompi bentukan Yotam Marchasam –seorang anak pendeta Kristen– berisikan pemuda-pemuda Kristen di wilayah Gunung Halu, Cianjur.
Pada 1946, Kompi Yotham bergabung dengan Batalion III pimpinan Mochamad Basyir. Keyakinan agama yang berbeda bukan penghalang mereka untuk berjuang bersama melawan penjajah. Pasukan inilah yang menjadi momok bagi tentara Inggris yang melewati jalur Cianjur-Bandung sejak akhir Desember 1945 hingga pertengahan 1946.
“Yang dipikirkan oleh pejuang Kristen itu bukan sekedar keyakinan atau agama. Mereka menomorduakan itu. Yang penting adalah mereka ikut aktif membebaskan negara dari kolonialisme bangsa lain. Meskipun para kolonialis itu beragama sama dengan mereka, mereka tidak peduli, bahkan mereka ikut berjuang dengan orang-orang yang secara keyakinan berbeda,” jelas Hendi.
Tapi, segelintir pejuang yang turun ke front juga termotivasi dengan alasan unik dan agak nyeleneh. Bagi mereka yang berjiwa nasionalis, adalah aib bagi seorang pemuda yang tidak berjuang menghadapi tentara Belanda. Secara psikologis, ada yang jadi pejuang karena tersinggung kejantannya dilecehkan dengan motto yang berlaku saat itu, “yang tidak ikut perang, bukan laki-laki”. Ada yang memang ingin menjadi tentara. Ada pula yang ingin terlihat gagah di depan cewek-cewek.
Begitupun setelah perang, orang-orang pejuang itu pun bermacam tindak tanduknya. Tidak dimungkiri ada yang pragmatis mencari peruntungan dari sepak terjang perjuangannya di masa perang. Kendati demikian, banyak pula yang memegang teguh idealisme bahwa perjuangannya adalah sumbangsih bagi bangsa dan negara. Alasannya sederhana, karena pada saat itu semua orang berjuang. Dan perjuangan di masa perang bukanlah sesuatu yang istimewa. Tidak heran bila kita menemukan veteran perang yang hidup dalam kemiskinan bahkan menolak mengajukan hak atas uang pensiun kepada pemerintah.
“Ini terkait sikap hidup. Kalau pejuang itu konsisten dengan tujuan perjuangannya, dia akan selalu memegang itu bahkan kemiskinan pun akan dia hadapi,” ujar Hendi.
Artikel ini telah terbit sebelumnya di website Historia.id