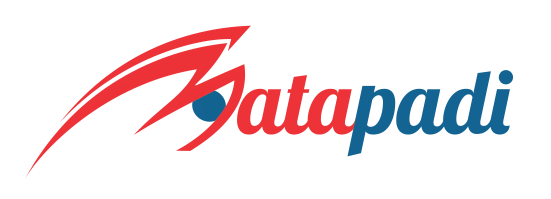Indonesia dan Bangsa Indonesia
October 27, 2020Nasionalis Indonesia Yang Radikal
November 2, 2020Surabaya: Media, Kekuasaan, dan Sejarah

Tampak Sutan Syahrir sedang berbicara dengan K’tut Tantri. Sumber: http://the-chantary.blogspot.com/2016/08/ktut-tantri-wartawan-amerika-yang.html
Pada 1945, publik di luar Indonesia memiliki akses yang sangat terbatas atas akses berita yang independen, terutama saat bulan-bulan awal turbulensi revolusi. Surat kabar berbahasa Belanda kembali muncul pada akhir 1945 dalam kendali penuh pemerintah. Karena Republik Indonesia baru saja diproklamasikan dan belum diketahui oleh bangsa-bangsa lain di dunia, para jurnalis Indonesia pun tidak serta-merta dapat mencapai pembaca dalam skala internasional.
Sebaliknya, bagi kolonial Belanda relatif mudah untuk mempengaruhi pendapat publik. Bagi mereka, prioritas utama adalah meyakinkan dunia internasional (khususnya para sekutu mereka) bahwa mereka berhak “menegakkan kembali hukum dan ketertiban” di kawasan yang disebut sebagai “koloni”. Sebagai contoh, pada saat itu, American United Press yang meliput kejadian di Indonesia nyaris tidak pernah melaporkan pengalaman langsung dari para korespondennya. Mereka tidak mendekati para jurnalis Indonesia, berbeda dengan Belanda yang sudah lama tinggal di Indonesia, para propagandis dengan mudah menciptakan gambaran negatif tentang Gerakan Kemerdekaan Indonesia.
Hanya beberapa tahun sesudahnya, sekitar tahun 1948, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mulai mengkritik kebijakan perang kolonial dari rekan Belanda mereka. Dengan motivasi di baliknya adalah kepentingan untuk menjadi penguasa tak langsung atas kekayaan alam Indonesia. Selain perusahaan Belanda, juga banyak perusahaan Amerika, Australia, dan Inggris yang berusaha mempertahankan akses atas kekayaan alam Indonesia. Nyatanya, Belanda bukan hanya sebagai sekutu, tetapi juga sebagai rival.
Belanda melakukan kampanye fitnah yang mempengaruhi media Inggris dan Amerika. Faktanya, keberadaan Radio Pemberontakan Bung Tomo membawa ancaman tersendiri atas kepentingan Belanda. Dia tidak hanya dibenci karena membakar semangat bangsanya untuk terjun dalam revolusi, tetapi juga ditakuti karena memberikan ruang bagi seorang wanita kulit putih untuk melakukan siaran dalam bahasa Inggris.
Ini berarti bahwa Radio Pemberontakan juga mencapai pendengar di luar orang-orang Indonesia. Nama kawan wanitanya ini tersembunyi dalam banyak nama, di antaranya ‘Ktut Tantri’, Miss Daventry Walker, juga sebutan ‘Surabaya Sue’ saat aktif di corong radio bersama Bung Tomo.
Pada 1945 dia memilih bergabung di pihak Republik yang baru lahir dan menjadi penyiar dari radio Bung Tomo. Radio Pemberontakan ini melakukan counter atas prapaganda Belanda dalam bahasa asing. Hal ini juga membuat frustasi pasukan Inggris yang tengah berupaya menduduki Surabaya. Dalam sebuah artikel bulan April 1946, penulis Indonesia, Idrus Sardi, menuliskan bahwa pasukan Inggris sampai memuat sayembara atas kepala pimpinan BPRI:
Sutomo tersenyum manis saat mendengarkan pengumuman Inggris. Ia tidak pernah menduga bahwa ia memiliki arti yang begitu penting. Ia tertawa lalu berkata kepada Ktut Tantri: ‘seandainya saja Inggris mau membayar seharga itu atas tiap orang Indonesia.’
Tentang Ktut Tantri, Idrus menambahkan:
Miss Daventry adalah seorang jurnalis Amerika. Sekalipun ia seorang wanita asing, ia tidak pernah merasa takut kepada Sutomo yang menyebut Inggris sebagai penjahat.

K’tut dalam berita koran Daily News, 14 Juni 1947. Sumber: http://ourindonesiatoday.blogspot.com/2016/10/amri-yahya-and-sydney-university-labor.html
Alfred van Sprang, selaku koresponden Belanda adalah contoh awal betapa negatifnya citra Sutomo dan Ktut Tantri yang dibuat dari sudut pandang Belanda. Van Sprang tinggal di Surabaya pada September dan Oktober, memulihkan diri pasca keluarnya dia dari kamp tawanan Jepang. Dia kemudian segera menjadi reporter dari American United Press dan menuliskan dalam bukunya Soekarno Lacht (Senyuman Sukarno, 1946):
Ktut Tantri adalah seorang yang buruk rupa, luar maupun dalam… Jika ia tidak sakit jiwa, dia tentu menderita histeria. Dengan rambut merah, kacamata besar, hidung yang runcing, ia memilih setia kepada Soekarno. Dengan lidahnya yang tajam ia adalah aset propaganda Indonesia yang berharga.[1]
Sebuah pertanyaan serius untuk patut untuk dipertanyakan, seberapa independen jurnalis Belanda seperti Van Sprang? Apakah mereka memiliki kebebasan menulis sisi positif dari pimpinan-pimpinan Indonesia seperti Sutomo?
Dalam sebuah artikel berjudul Terug naar Patria en de Bladen laten verrekken (Kembali ke Patria dan Tinggalkan Kertas-kertas di Belakang, 2005), sejarawan Belanda, Angelie Sens, menggaris bawahi bahwa jurnalis Belanda yang pertama aktif di kawasan itu berada dalam pengawasan langsung rezim kolonial yang sedang sibuk menancapkan kukunya kembali. Surat kabar Belanda Het Dagblad diterbitkan pertama kali pada 23 Oktober 1945, didistribusikan secara gratis dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah.[2]
Bagaimana sensor ini bekerja, telah dianalisa oleh sejarawan Belanda, Louis Zweers, dalam studinya, De gecensureerde oorlog; Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949 (Perang Sensor; Tentara Melawan Media di Hindia Belanda 1945-1949), dan diterbitkan pada tahun 2013. Menurut Zweers, kebanyakan reporter Belanda jarang sekali meninggalkan hotelnya. Mereka hanya mengunjungi undangan dan konferensi pers dengan mendapatkan sumber informasi dari jalur diplomatik, militer dan pemerintah. Jurnalis Belanda sering dihambat dalam pengecekan fakta.
Ia menyimpulkan bahwa output dari para jurnalis pada masa itu dipenuhi dengan propaganda yang membenarkan aksi militer Belanda: “Banyak jurnalis Belanda yang patuh dan menurut… dan banyak surat kabar nasional tak lebih dari corong suara partai politik.”
Surat kabar sayap kiri di Belanda yang melakukan tekanan balik atas propaganda, tidak mampu mencapai pembaca dalam jumlah besar dan biasanya dibubarkan dengan tuduhan “kawan dari Soekarno”. Zweers menuliskan:
Para komandan pasukan terkadang melarang anggotanya untuk membaca surat kabar Harian maupun Mingguan dari kelompok sayap kiri yang senantiasa mengkritisi kebijakan Belanda di Indonesia (dan bahkan surat kabar mereka tidak didistribusikan di Batavia).
Koresponden Amerika yang terkenal, Martha Gellhorn misalnya, menulis bahwa Bung Tomo adalah pimpinan pemberontak yang haus darah, ia juga menuliskan: “Sekalipun ia bergigi indah, matanya tampak marah dan memiliki tangan seperti cakar. Dari sudut pandangnya, para interniran Belanda yang diungsikan pasukan Indonesia dari Surabaya ke daerah pedalaman dalam keadaan disandera dan diabaikan hingga mati, bukan karena kekejaman tetapi karena ketidak efisienan.”[3] Jurnalis Australia Alan Dower bahkan menyebutkan Bung Tomo bertanggung jawab secara pribadi atas ketegangan dan kekacauan di Indonesia termasuk disanderanya ribuan Belanda dan Indo.
Sejarah selalu dapat dijadikan pelajaran. Dan, untuk hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apa “kebenaran” yang dituliskan hari ini? Kekuasaan siapa yang berada di baliknya?[]
[1] Alfred van Sprang, En Soekarno lacht…! The Hague: W. van Hoeve, 1946., hlm. 69-71.
[2] Angelie Sens, Terug naar Patria en de Bladen laten verrekken (2005) pp.
[3] Martha Gellhorn, The Face of War, New York: Atlantic Monthly Press, 1994., hlm. 197.