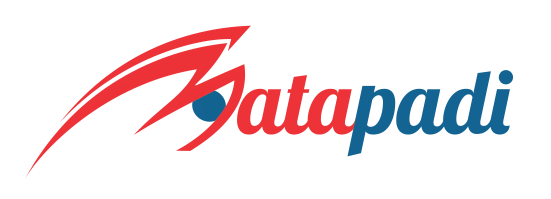LORENG PERTAMA TNI, BATALION RUKMAN
May 24, 2022HARI AKHIR SANG PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
June 15, 2022DARI KEBUN SAMPAI BEKAS GEDUNG VOLKSRAAD

Di kebun belakang, beberapa bulan lalu, Fatmawati melihat suaminya termenung. Mata suaminya menatap langit, mungkin menghitung bintang. Zuz Fat tak mau mengganggu. Berhari-hari ini suaminya sibuk dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
“Besok Mas akan mengucapkan pidato yang amat penting mengenai dasar-dasar negara kita jika merdeka kelak,” ucap suaminya yang seketika sudah berada di dalam kamar. Zuz Fat teringat dengan pertanyaan Radjiman Wediodiningrat yang belum terjawab, “Negara yang kita bentuk itu apa dasarnya?” Langit semakin gelap. Fatmawati ingin tidur senyenyak Guntur.
Juni 1945, masih tanggal satu. Zuz Fat menemani suaminya. Di bekas gedung Volskraad itu ia duduk terpisah. Di balkon lain, orang-orang Jepang tak melepas pandangan. Zuz Fat pun memandang suaminya melangkah ke podium. Ia meneguhkan suaminya yang sempat melirik sekilas.
“Allah Swt membuat peta dunia. Seorang anak kecil pun—jikalau dia melihat peta dunia—dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan kepulauan di antara Samudera Pasifik dan Lautan Hindia dan di antara Benua Asia dan Australia. Bangsa Indonesia, karena itu, meliputi semua orang yang bertempat tinggal di seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang di ujung utara Sumatera sampai Merauke di Papua.”
Zuz Fat mendengarkan suaminya menyebut mutiara pertama, Kebangsaan.
“Itu bukanlah Indonesia Uber Alles. Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Ingatlah kata-kata Gandhi, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaanku adalah perikemanusiaan. My nationalism is humanity,” suaminya berkata meyakinkan.
“Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.”
Zuz Fat terbawa suasana, ikut bertepuk tangan.
“Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip satu dan prinsip dua, yang pertama-tama saya usulkan kepada Tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.”
Zuz Fat mencatat mutiara kedua, Internasionalisme. Mutiara ketiga? Zuz Fat menarik napas. “Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan,” terang suaminya.
Mutiara keempat adalah kesejahteraan sosial. “…jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan economie kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya,” suaminya berkata mantap.
“Saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan empat prinsip: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme,—atau perikemanusiaan, 3. Mufakat,—atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
Zuz Fat tersenyum bangga. Tepuk tangan riuh membahana.
“Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indera. Apalagi yang lima bilangan?”
“Pandawa lima,” Zuz Fat mendengar celetukan seorang dalam ruangan.
“Pandawa lima pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi—saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa—namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”
Di tengah tepuk tangan seisi ruangan, Zuz Fat meresapi pidato suaminya. Tak sepakat dengan lima mutiara, suaminya menawarkan Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. “Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong’.”
“Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada Tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: Trisila, Ekasila atau Pancasila?” suaminya menawarkan pilihan.
Ruangan sidang bergemuruh. Tepuk tangan riuh. Hati Zuz Fat ceria. Pidato suaminya yang lebih dari sejam itu masih perlu dipikirkan. Suaminya duduk dalam panitia kecil bersama Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin.
Kelak, Zuz Fat mengetahui, yang disepakati mereka adalah Pancasila, bukan peras-perasan Trisila atau Ekasila.
“Bagaimana pidato Mas, Fat?” tanya suaminya dalam perjalanan pulang naik mobil.
“Hebat sekali!”
Setiba di rumah, Zuz Fat langsung menuju kamar Guntur yang dititipkan ke kakek-neneknya. Usai sembahyang Dzuhur, mereka pun makan bersama. “Siang itu,” ujar Zuz Fat, “Bung Karno dengan muka berseri-seri makan dengan lahap sekali.” Wajah cilik Guntur terlihat menggemaskan.
(Kutipan dari buku Dari Krakatau Sampai Akhir Hidup Sukarno, Matapadi Pressindo)