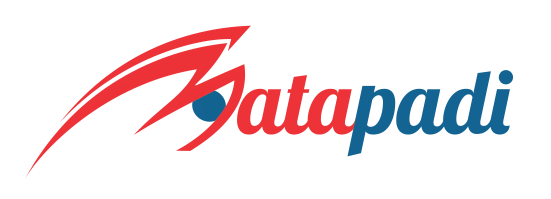Pasukan Siliwangi, Patriotisme Melampaui Tapal Batas
October 29, 2019Melawan Gerilya, Jenderal Simon Spoor
December 24, 2019Perang Teritorial
Perang Teritorial menjadi teori strategis pertempuran Indonesia paska Agresi Militer Belanda pertama. Di masa itu, dengan angkatan perang yang belum ada dan tentara yang terbina baik, tidak mungkin Indonesia menghadapi amunisi Belanda secara frontal. Dan, juga tidak mungkin kalau tidak kontak senjata dengan Belanda.
Setelah mendapat boncengan dari Inggris, melalui jalan agresi Belanda berhasil merangsek menduduki kota-kota di Jawa Barat dalam tempo cepat tanpa mendapat halangan berarti. Walau demikian daerah-daerah di pegunungan dan pedesaan tetap tidak jatuh dibawah kontrol Belanda.
Oleh karena itu, siasat efektif yang dikembangkan Kolonel A. H. Nasution sebagai panglima regional Divisi Siliwangi, justru membiarkan tentara Belanda masuk ke kota lalu mengepungnya dari luar. Tujuan dari strategi ini adalah menguras sumber daya milik militer Belanda yang kemudian terpencar-pencar di setiap kota dan sibuk digunakan untuk mempertahankan kantong kedudukannya sendiri-sendiri.
Alhasil, Belanda kepayahan, dan baru merasa lega ketika Persetujuan Renville ditandatangani. Kurang lebih 40.000 anak-anak Siliwangi dan juga semua perabot pemerintahan Republik angkat kaki dari Jawa Barat.
Dalam analisanya Kolonel A. H. Nasution juga mengungkapkan bahwa topografi alam serta kultur masyarakat Indonesia harus dimanfaatkan sebagai basis utama dalam menjaga dan terus membina kekuatan. Hasil pemikirannya itu pun disambut baik oleh oleh Panglima Sudirman. Bahkan, Presiden Sukarno berkata akan pergi memimpin sendiri gerilya kalau betul Belanda melancarkan kembali agresi militer.
Nampaknya mata maupun telinga Belanda dapat mengetahui ide tersebut, disamping mereka juga pernah merasakan bahaya yang diakibatkannya. Maka tidak perlu mengulur waktu lagi dalam mengambil keputusan. “Kepala ular” harus cepat dipotong sebelum tubuhnya makin memanjang dan menambah kuat belitannya. Kebetulan juga pecah Madiun Affair.
Secara kilat “Operatie Kraai” diterjunkan guna mematuk langsung kepala Republik di Yogyakarta. Sekali lagi, militer Belanda berhasil menunjukkan keunggulannya dalam agresi. Cukup hitungan jam ibukota Republik sudah dikuasai.
Akan tetapi, Sukarno yang semula diperkirakan bakal meronta dan melawan sehingga membuka jalan provokasi bagi tindakan tembak di tempat tidak terjadi. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, bersama sejumlah petinggi Republik justru membiarkan dirinya ditangkap. Sama sekali tidak ada gerakan panik atau perintah lawan atas penyerbuan ke Gedung Agung.
Jenderal Spoor pusing. Kepala yang menjadi sasarannya tidak sampai ditumpas. Selain itu, walau Sukarno-Hatta sudah dapat dipisahkan dan diasingkan dari rakyatnya, perlawanan tetap bangkit dimana-mana, termasuk muncul tekanan dari luar negeri. Berita-berita yang disebarkan tentang berhasil ditawannya pemimpin Republik juga bukan menjadi propaganda yang mematahkan tetapi malah menjadi kabar yang memancing penentangan banyak pihak.
Di depan Dewan Keamanan PBB, L. N. Palar mengatakan bahwa kelakuan Belanda ini adalah Pearl Harbour jilid dua. Maka, dibawah ancaman putusnya Marshall Plan yang disuarakan oleh salah seorang senator karena menganggap Belanda juga telah menghina Amerika dengan melakukan penyerangan meski utusan PBB masih berada di Yogyakarta, tidak lagi ada yang bisa diperbuat untuk menyelamatkan muka dari sorotan publik internasional. Belanda yang baru saja menjerit karena dilindas Nazi, sesudah lepas malah melancarkan aksi serupa.
Melalui diberlakukannya Perintah Siasat No.1, strategi perang teritorial dan taktik tempur gerilya TNI terbukti mampu menjaga eksistensi Republik, bahkan sekaligus memecah orientasi pendudukan yang dijalankan oleh Belanda. Mereka kehabisan akal sehat dan malah mengadakan pembersihan ke desa-desa sehingga umumnya masyarakat jadi makin antipati.

(www.verzetsmuseum.org)
Sementara itu, bersama rakyat, dari desa ke desa, Panglima Sudirman turun gelanggang tetap memimpin TNI. Di kota Yogyakarta sendiri, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak bekerjasama apalagi tunduk pada Belanda. Di Sumatera, Syafruddin Prawiranegara melanjutkan estafet pemerintahan dengan dukungan militansi total dari Aceh, sehingga dapat terpantau dari Delhi dan sampai ke forum di PBB bahwa Republik Indonesia tetap ada sebagai negara. Begitu pula segenap rakyat di berbagai pulau yang setia kepada pimpinan daerahnya masing-masing tetap menghendaki Belanda keluar dari Indonesia. Sultan Hamid II menyatakan tidak bersedia melakukan konferensi inter-Indonesia dengan Belanda apabila kedudukan Republik ditiadakan.
Belanda, yang kadung mengumumkan bahwa Republik sudah tidak ada sehingga tidak lagi perlu menganggap penting perundingan-perundingan maupun persetujuan yang diadakan sebelumnya, apalagi membuat memorandum kesepakatan baru, juga dibuat tercengang oleh Serangan Umum ke Yogyakarta. Serangan ini seolah menjadi terompet nyaring yang mengisyaratkan bahwa Republik tetap bergerak, tidak padam.
Belanda stres. Mereka terkepung lagi dan malah makin terisolasi. Prajuritnya kelelahan. Politisinya kebingungan. Sumber dayanya tekor habis-habisan.
Mereka salah membaca musuh. “Burung Gagak” yang dilepaskannya ternyata cuma berhasil mematuk satu kepala Republik. Padahal, bangsa ini memiliki ribuan kepala yang dihidupi oleh satu jiwa yang sama, jiwa yang bernama merdeka.
Patah tumbuh hilang berganti. Esa hilang dua terbilang. Otak Belanda terlalu asing sehingga gagal paham terhadap realita yang menjadi makna dari adanya kalimat-kalimat semacam itu.