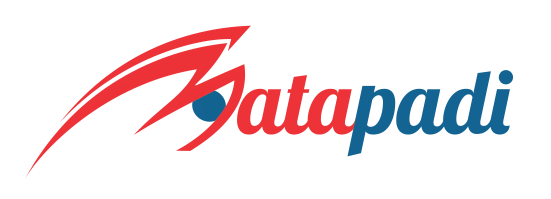Melawan Gerilya, Jenderal Simon Spoor
December 24, 2019Ir. Djuanda
December 24, 2019PRRI/PERMESTA (Bukan) Pembangkang
Memasuki bulan terakhir 1956 perselisihan yang terjadi di antara sejumlah perwira tinggi militer semakin bertambah tajam. Bahkan sampai melebar ke luar Jawa dimana sebagian panglima bisa mengandalkan dukungan massa tradisional dan warga setempat. Dan, keadaan makin tidak menentu ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang dianggap sebagai eksponen utama dari luar Jawa di dalam pemerintahan pusat, pada 1 Desember 1956 menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri.
Bung Hatta merasa sudah tidak bisa lagi menjalin kerjasama dengan Bung Karno. Akibatnya, Dwitunggal yang selama ini menjadi ikon perjuangan dan kemerdekaan semesta Indonesia justru nampak sebagai suatu krisis kepemimpinan yang pecah. Sedangkan di masa itu berbagai macam keterbatasan telah pula menambah beban pemerintah.
Pengelolaan administrasi keuangan tidak pernah berlangsung teratur. Selain itu berbelitnya prosedur yang harus ditempuh untuk memperbaiki ekonomi masyarakat juga mengantarkan buah permasalahannya sendiri. Sebagian panglima di luar Jawa, yang jauh dari markas besar, menempuh jalan pintas dalam usahanya menekan pemerintah pusat. Dengan dalih upaya untuk memakmurkan daerah, mereka pun mengorganisir aksi penyelundupan.
Kemelut yang sudah berkepanjangan itu digambarkan oleh seorang diplomat senior Indonesia, Dr Ide Anak Agung Gde Agung.
“Perasaan tidak puas dari berbagai daerah semakin bertambah ketika mereka mulai mengetahui tak kurang dari 71% pendapatan luar negeri sesungguhnya berasal dari hasil ekspor setempat, khususnya dari Sumatera. Sedangkan pembangunan setempat terasa ditelantarkan oleh pemerintah pusat. Ini mendorong lahirnya gerakan-gerakan di sejumlah daerah, dengan dukungan kuat para panglima militernya, untuk membangun daerah mereka sendiri tanpa menunggu alokasi dari pusat.”
Berawal dari daerah yang kini bernama Sumatera Barat, aksi pembangkangan turut meluas ke daerah lain. Para penguasa di Padang membentuk apa yang dinamakan “Dewan”. Suatu lembaga baru yang dipimpin oleh panglima militer setempat, dengan tujuan mengambil alih pemerintahan sipil. Dewan ini bertujuan membangun daerahnya dengan memanfaatkan hasil setempat. Dan, tentu saja langkah seperti ini sudah merupakan tantangan terbuka kepada kewenangan pemerintah pusat.
Selanjutnya, lahir satu demi satu Dewan. Dimulai dari Dewan Banteng di Padang pada pertengahan tahun 1956 yang dipimpin oleh Letkol Achmad Hussein. Lalu muncul Dewan Gajah di Medan di bawah pimpinan Kolonel Simbolon, dan Dewan Garuda di Palembang yang dipimpin Letkol Barlian di awal 1957. Sampai kemudian, di bulan Maret 1957, lahirlah Permesta (Perjuangan Semesta) yang berada di dalam pimpinan Kolonel Ventje Sumual dengan pusatnya di Makassar.
Tantangan keras yang pertama muncul dari Dewan Banteng pada November 1957. Dewan ini meminta perbaikan radikal dalam semua bidang, terutama dalam tubuh Angkatan Darat dan kepemimpinan negara. Dan, merasa tuntutannya tidak pernah memperoleh tanggapan serius, situasi pun menggelinding ke arah konflik terbuka.
Piagam Djogja, yang dihasilkan dari pertemuan tidak kurang 270 orang perwira selama tanggal 17 hingga 23 Februari 1955 dengan antara lain berisi kesepakatan dari seluruh unsur pimpinan TNI AD untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, hanya menjadi sekedar selembar kertas sejarah. Nampaknya, perbedaan di antara para panglima militer memang sudah sangat sulit untuk kembali disatukan.
Puncak pembangkangan meletus pada 10 Februari 1958. Secara terbuka Achamad Hussein menuntut pengunduran diri Kabinet Juanda. Ultimatum ini langsung ditolak oleh pemerintah pusat.
Enam hari kemudian, dengan mengandalkan dukungan dari sebagian kesatuan militer di wilayah Sumatera Tengah, Tapanuli serta Sulawesi bagian Utara dan Tengah, Achmad Hussein mengumumkan terbentuknya pemerintah tandingan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).
Belum genap 10 tahun dari Proklamasi Kemerdekaan, sebuah perpecahan ternyata tidak lagi bisa dihindarkan. Upaya untuk menghindarkan diri dari konflik terbuka menjadi berantakan dan harus diselesaikan melalui operasi militer dari pusat.
Dari sini, renungan dan pemikiran yang diungkapkan Jenderal A.H. Nasution di tahun 1953 tentang ancaman yang menghantui sebuah negara menemukan buktinya. “…Dalam Negara yang ditimpa oleh perpecahan, korupsi, kemelaratan dan sebagainya, tiada dapat diharapkan bahwa rakyat mau bergerilya mempertahankannya terhadap agresor dari luar, malahan rakyat akhirnya akan bergerilya terhadap pemerintahannya sendiri.”
Dan, soal Permesta, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution di Tomohon pada 1961 menyatakan sendiri, TNI dan Permesta tidak ada yang menang.
“Sesudah keluar keputusan amnesti dan abolisi beramai-ramai anggota Permesta keluar dari hutan-hutan seperti Kolonel D.J. Somba, Mayor Jenderal A.E. Kawilarang, Kolonel Dolf Runturambi, Kolonel Petit Muharto Kartodirdjo, dan Kolonel Ventje Sumual beserta pasukannya menjadi kelompok paling akhir yang keluar dari hutan-hutan.” Demikian ungkap Frans Pangkey, mantan pengawal pemimpin Permesta, Alex Kawilarang, yang kemudian turut berjibaku dalam Operasi Trikora.()
Sumber: Benny Moerdani, Profil Prajurit Negarawan; Pokok-Pokok Gerilya; https://manado.tribunnews.com/2019/10/01/kisah-eks-permesta-di-belantara-papua-bunuh-tentara-belanda-tanpa-kehilangan-satupun-anggota?page=all