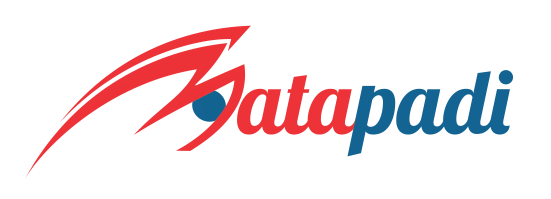Perang Sunggal, Perjuangan Soal Martabat dan Kedaulatan
March 26, 2020Natsir, Orde Baru dan Petisi 50
April 2, 2020Mengenang Dwi Tunggal Di Surabaya, Oktober 1945
“… Kami tidak memulai pertempuran Surabaya, tetapi ketika kelihatan kami akan menang, orang Inggris bergegas memanggil Sukarno untuk menyelamatkan mereka…”.
Rangkaian Pertempuran Surabaya 1945 terkenang dalam memori Sukarno dengan kata: keji, ganas, dan tak terlupakan. Suatu bencana di bagian timur Pulau Jawa yang meletus beberapa minggu setelah Panglima Revolusi itu mensyahkan keberadaan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Dalam memori Sukarno, Surabaya di ujung Oktober 1945, merupakan arena pertempuran besar pertama bagi tentara Republik. Demikian pula dengan Hatta, ia mengenang Pertempuran Surabaya sebagai peristiwa yang penuh keberanian, pengorbanan, sekaligus mengerikan. Rakyat bergerak tak terkendali, menyerang setiap pihak yang dirasa mencurigakan.
Kedatangan Batalyon Ayam Jago
Indonesia, baru saja memproklamasikan Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara yang belia ini harus menghadapi ujian, menyambut kedatangan sang pemenang Perang Dunia II, Sekutu. Pasukan Sekutu yang diwakili oleh tentara Inggris itu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945.
Beberapa hari sebelumnya, telah datang pesan kawat dari Amir Sjarifuddin, Menteri Penerangan, yang kelak juga mendampingi Sukarno dan Hatta di Surabaya. Kawat Menteri Penerangan itu berisi pesan bahwa, tanggal 25 Oktober 1945, akan mendarat tentara Inggris atas nama Sekutu dengan tiga tujuan :
- Melindungi dan mengungsikan para tawanan perang dan kaum interniran.
- Melucuti dan memulangkan tentara Jepang.
- Memelihara ketertiban dan keamanan umum.
Tiga tuntutan yang disampaikan melalu kawat Menteri Amir itu dirasa cukup mudah untuk disanggupi, ditambah perintah untuk menerima Sekutu dengan baik.
Namun, sikap yang ditunjukkan pihak Sekutu ketika akan memulai pendaratan justru membuat semuanya menjadi bermasalah. Sehingga pendaratan awal para serdadu Inggris di Surabaya itu tidak berjalan mulus.
Hario Kecik, dalam memoarnya menyebutkan: sempat terdengar desas-desus bahwa pada tanggal 24 Oktober 1945, pihak Sekutu sudah mulai bersiap mendarat di Surabaya. Namun upaya pendaratan ini mendapat penolakan oleh pihak Republik. Terkesan memaksa, dan berkali-kali terjadi perundingan namun tak kunjung menemukan kata sepakat.
Hingga pada tanggal 26 Oktober 1945, dalam catatan Roeslan Abdulgani, secara berangsur-angsur pasukan Sekutu mulai memasuki Surabaya. Sementara menurut A.J.F. Doulton dalam bukunya The Figting Cock: pada tanggal 25 Oktober 1945 sore hari, waktu Surabaya, pihak Inggris secara berangsur-angsur bergerak memasuki Surabaya melalui sekitaran Kali Mas.
Niatan Sekutu mendarat di Surabaya itu pada akhirnya memang mendapat jalan.
Selanjutnya, Surabaya mulai menyambut tamu dari seberang. Awalnya tampak biasa. Semua berjalan cukup tenang, meski kemudian sikap jumawa para serdadu pemenang Perang Dunia II itu mulai tampak.
Persetujuan demi persetujuan dicapai, kelonggaran diberikan, tamu dari seberang itu kemudian diperkenankan menggunakan beberapa fasilitas yang ada.
Tindakan yang diambil pihak Sekutu selanjutnya justru mengundang amarah rakyat. Keleluasaan yang diberikan oleh Surabaya, justru dibalas dengan sikap pongah Sekutu. Kesempatan menggunakan gedung-gedung penting menjadi celah untuk membangun titik-titik pertahanan, sekaligus sebagai persiapan untuk menggempur ‘tuan rumah’ dari dalam.
Dari sini tampak pula bahwa, Inggris semakin nyata akan mendudukkan Belanda kembali sebagai penguasa. Saat itu, dalam perwakilan Sekutu juga terdapat orang-orang Belanda.
Hanya beberapa waktu berselang, pihak Inggris mulai mengkhianati kesepakatan. Mereka menyebarkan pamflet melalui pesawat Dakota yang berisi seruan perintah untuk menyerahkan semua senjata rakyat Surabaya yang telah direbut dari tangan tentara Jepang. Jika menolak dan kedapatan membawa senjata maka akan ditembak di tempat.
Seruan ini jelas memancing amarah arek-arek Surabaya. Martabat dan kedaulatan rakyat Surabaya terkoyak. Harga diri rakyat Surabaya itu dilecehkan oleh para serdadu yang sombong karena menjadi pemenang Perang Dunia II.
Namun, bukan senjata-senjata yang diserahkan, melainkan sikap penolakan yang tegas. Surabaya bersiap melawan. Seruan didengungkan, nyali dan semangat dikobarkan.
Dipicu pada peristiwa sekitar tanggal 27 Oktober 1945. Sebuah drum yang berada di depan Rumah Sakit Darmo tertabrak oleh rombongan pemuda Sulawesi (PRISAI). Kaget dengan insiden kecil ini pihak tentara Inggris yang berjaga bereaksi dengan mengeluarkan tembakan yang mengarah ke rombongan pemuda Sulawesi itu.
Tembakan kemudian dibalas dengan tembakan. Tanggal 28 Oktober 1945, dilancarkan serangan besar-besaran terhadap kedudukan Inggris di Surabaya. Seluruh kekuatan bersenjata di Surabaya Bersatu. Serbuan ini di luar perhitungan Inggris.
Peristiwa ini kelak dikenal dengan Pertempuran Tiga Hari. Beberapa sumber menyebutkan pertempuran ini terjadi dalam kurun waktu 28, 29 dan 30 Oktober 1945. Sementara yang lainnya, menyebut bahwa peristiwa ini bermula tanggal 27 Oktober hingga 29 Oktober 1945.
Ketika pertempuran masih berlangsung, kondisinya semakin tidak terkendali. Arek-arek Surabaya sebagai ‘tuan rumah’ jelas lebih paham seluk beluk kota, sehingga dengan leluasa menguasai jalannya pertempuran fase pertama itu. Saluran listrik, air, hingga telepon dirusak, juga sabotase terhadap suplai bantuan logistik dan pasukan.
Pada pertempuran yang merupakan petaka itu, tentara Inggris itu dengan terpaksa mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Mereka sejatinya malu, sebagai pemenang berbagai palagan dalam Perang Dunia II, dengan terpaksa bertekuk lutut oleh kekuatan rakyat biasa dengan kemampuan tempur jauh di bawah mereka.
Mereka terkepung. Akhirnya, demi keselamatan sekaligus menyelamatkan muka sombong mereka, pihak Inggris meminta bantuan dari para pemimpin Republik yang ada di Jakarta.
Mereka meminta kepada Sukarno dan Hatta sebagai pimpinan Republik Indonesia, untuk meredam kemarahan rakyat Surabaya, sekaligus meminta gencatan senjata.
Dwi Tunggal dan Surabaya 1945
Kabar itu akhirnya sampai ke ujung telepon yang diterima oleh Tukimin, pengawal pribadi Presiden Sukarno. Surabaya bergolak, rakyat mengamuk, darah mengalir deras, serdadu Sekutu silih berganti meregang nyawa, suasana liar tak terkendali.
Pengawal pribadi Sukarno menyampaikan kabar yang datang tengah malam itu kepada tuannya. Pikiran Sukarno mulai kacau, namun tak ada keluh yang ia sampaikan pada Fatmawati, istrinya, apalagi Tukimin. Masih setengah tersadar, sambil melanjutkan tidurnya, Sukarno berkata bahwa besok ia akan terbang menuju Surabaya.
Tanggal 28 Oktober 1945, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Penerangan, terbang ke Surabaya mengunakan pesawat terbang milik Inggris. Sampai di Surabaya, kekacauan tampak jelas di hadapan rombongan pimpinan Republik dari Jakarta itu.
Pihak Sekutu yang tak kuasa menghadapi keberanian rakyat Surabaya, mulai sedikit lega. Mereka rela bersusah payah mendatangkan pimpinan Republik Indonesia itu karena memang sudah tak berdaya, terkepung keberanian rakyat Surabaya.
Sukarno mengenang, kota Surabaya waktu itu sangat kacau. Hampir di setiap penjuru jalan terjadi perkelahian berdarah. Mayat bergelimpangan – beberapa di antaranya bahkan tanpa kepala, setiap orang tanpa ragu akan menyongsong pertempuran. Sekalipun dengan senjata yang seadanya.
Dalam otobiografinya, Penyambung Lidah Rakyat, Sukarno menggambarkannya sebagai berikut :
“… Di tengah-tengah selokan, tepat di depan markas-besar tentara Inggris, seorang Jawa yang sudah tua berlumuran darah berdiri tegak kaku. Kedua belah tangannya yang berbuku-buku diangkat setinggi dada dan memegang sebilah keris. Dia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Hanya memegang kerisnya dengan erat, daun keris itu tertuju ke bawah, ia mendoa, tanpa ragu-ragu yakin akan kekuatan gaib dan mengalirkan kekuatan keris itu ke dalam tubuhnya. Ini adalah cara ia berjuang…”
Kekacauan tersebut juga tampak dalam pandangan Hatta ketika baru saja mendarat di Surabaya. Seorang Mayor tentara Sekutu yang sedianya mengantarkan rombongan menuju tempat perundingan, hampir ditusuk dengan bambu runcing oleh seorang pemuda.
Awalnya, terdapat kabar radio yang menyebutkan rencana kedatangan sang Dwi Tunggal ke Surabaya. Namun kabar itu tak dipercaya oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, Lapangan Terbang Morokrembangan diserbu oleh rakyat dan pesawat yang ditumpangi oleh Dwi Tunggal itu akan menjadi sasaran tembak.
Hingga akhirnya Sukarno keluar pesawat dan melambaikan tangan pada rakyat Surabaya yang sudah mengepung.
Akhirnya, kedatangan para pemimpin besar dari Jakarta itu disambut penuh antusias oleh rakyat Surabaya. Hatta mengenang, di antara rakyat yang menyambut kedatangan mereka, ada yang datang mendekatinya seraya berkata:
“Radio Inggris tadi pagi menyiarkan bahwa hari ini Bung Karno dan Bung Hatta akan datang ke Surabaya menolong menyelesaikan konflik antara tentara Inggris dan pasukan rakyat Indonesia, tetapi kami mula-mula tidak percaya. Tetapi setelah bung berdua beserta Menteri Keamanan mendarat tadi, mulailah kami percaya. Kami yakin, bung bertiga akan membawa kebaikan bagi rakyat Surabaya”.
Jelas sudah jika Sekutu benar-benar membutuhkan “tangan dingin” para pemimpin Republik Indonesia. Mereka didatangkan untuk meredam kemarahan dan kekacauan yang terjadi di Surabaya. Kedatangan para pemimpin nasional itu memberikan dampak yang amat signifikan. Jika tidak, tentara Sekutu yang terkepung itu akan dibantai arek-arek Suroboyo.
Pihak Inggris, sebagaimana dituturkan oleh Sukarno, sangat baik dalam memperlakukan para pemimpin nasional itu. Hal ini menjadi wajar bila melihat posisi Inggirs dalam kekacauan yang terjadi di ujung Oktober 1945 di Surabaya. Inggris sepertinya tak ada pilihan, selain harus “berbaik-baik” dengan pimpinan Republik.
Perjalanan dari Lapangan Terbang Morokrembangan menuju kediaman Residen Sudirman membutuhkan waktu kurang lebih empat puluh lima menit. Di sana, juga sudah banyak rakyat yang menunggu.
Tak berapa lama kemudian, rombongan ini bergegas menuju Kantor Gubernur Surabaya untuk melakukan perundingan dengan pihak Inggris. Celakanya, kedatangan rombongan pimpinan Republik Indonesia tak serta merta membuat kondisi langsung berubah kondusif.
Seperti yang dikenang Hatta ketika itu, terlihat beberapa rakyat Surabaya berusaha membakar markas Jenderal Mallaby, pimpinan tentara Sekutu, yang terletak tidak jauh dari jembatan kereta api, dekat kantor gubernur. Dengan sigap, Hatta memerintahkan agar api segera dipadamkan.
Pihak Republik dan Sekutu akhirnya memulai perundingan. Setelah saling memberi salam, kedua belah pihak duduk berkeliling pada sebuah meja. Sukarno memulai pembicaraan, kemudian Mallaby mulai menyampaikan perihal kedatangan pasukan Sekutu dan soal ultimatum Jenderal Hawthron melalui selebaran yang mendapat perlawanan.
Ultimatum inilah yang kemudian membuat arek-arek Suroboyo geram. Mereka merespon dengan perlawanan, hal ini juga disampaikan Mallaby kepada Sukarno.
A.J.F. Doulton dalam bukunya The Fighting Cock menuliskan: rakyat Surabaya marah, pos-pos pasukan Inggris dikepung, bahkan hingga tengah malam, tidak sedikit pasukan Inggris yang tewas. Namun anehnya rakyat Surabaya tidak mempedulikan berapa jumlah korban yang gugur, bila satu di antara rakyat tumbang di garis depan, maka segera datang bala bantuan dari belakang.
“Kami, pasukan Inggris yang di bawah komando-ku, bersedia berdamai. Sebab itu, pimpinan tentara Inggris di Jawa meminta pertolongan tuan-tuan untuk mencapai perdamaian.” Ucap Mallaby -sebagaimana dikenang oleh Hatta.
Pertemuan itu kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan yang disetujui secara lisan. Intinya, akan dilakukan pemulihan stabilitas keamanan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut, rencananya, akan dilaksanakan setelah dua hari pasca penandatanganan oleh kedua belah pihak.
Selama kedatangan para pemimpin nasional, setidaknya, sempat terjadi gencatan senjata dalam beberapa saat, meskipun di beberapa sudut kota masih terjadi beberapa insiden. Para pemimpin nasional dan pihak Inggris menyetujui untuk dilaksanakan gencatan senjata. Setelah persetujuan disepakati, kedua belah pihak melakukan pemeriksaan dengan berkeliling kota Surabaya. Mereka menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan oleh pihak Inggirs.
Para pemimpin nasional ini melakukan upaya untuk meredam kecamuk yang terjadi dengan berkeliling kota dan menyerukan agar rakyat segera menghentikan pertempuran. Bahkan ketika Sukarno sedang berbicara di depan arek-arek Suroboyo, suara ledakan dan letupan senapan masih saja terdengar, sebagaimana ia menuturkan:
“… Seorang pemuda yang berumur kira-kira enam belas tahun berdiri dekatku, memegang senapannya tegak lurus, dan menampung setiap kata yang keluar dari mulutku. Ketika aku mengatakan sesuatu semangatnya meluap, dan… DORRR! senapan terkutuk itu meletus! Dan lagi tepat di belakang telingaku. Aku terus berkeliling satu hari dan satu malam meneriakkan, ‘Hentikan pertempuran!’. Kita mengadakan genjatan senjata dan tetaplah di tempat masing-masing. Jangan menembak. Itu perintah saja. Hentikan pertempuran segara…”
Setelah selesai melakukan perundingan dengan pihak Inggirs, Dwi Tunggal beserta Menteri Amir segera kembali menuju Jakarta. Surabaya benar-benar diliputi semangat revolusi. Dalam perjalanan menuju lapangan terbang, Hatta mengenang :
“… Kami bertiga, Sukarno, Amir Syarifuddin, dan aku, pamitan dengan gubernur, residen, dan pemimpin-pemimpin yang lain di Surabaya. Sesudah itu, dengan suatu jip kami dan Jenderal Hawthron berangkat ke lapangan terbang. Pada suatu tikungan kami melihat di pinggir jalan seorang anak muda kira-kira berumur 12 tahun bersandar kepada sebuah tembok sedang tertidur dengan
menyandang sebuah senapan di bahunya. Melihat itu, Jenderal Hawthron berkata, ‘This is Revolution’…”
Namun, sebelum Residen Sudirman dan Mallaby mampu menemukan cara yang tepat untuk memberitahukan hasil perundingan pada rakyat Surabaya, bencana lebih besar justru datang tak terduga
Tidak lama setelah kepulangan menuju Jakarta, kabar buruk kembali diterima oleh Dwi Tunggal. Sebuah peristiwa yang kemudian menjadi alasan bagi Sekutu memborbardir Surabaya. Sebuah peristiwa yang menjadi rentetan besar meledaknya Pertempuran 10 November 1945. Kabar tersebut adalah kematian Mallaby.
Joe Pradana
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Sumber bacaan :
- Abdulgani, R. 1980. Seratus hari di Surabaya. Jakarta: Yayasan Idayu
- Adam, C. 1966, Bung Karno: Penjambung Lidah Rakjat Indonesia. Jakarta, Gunung Agung.
- Adam, C. 2014, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta. Yayasan Bung Karno
- Doulton, A.J.F. 2002, The Fighting Cock: Being the History of The 23rd Indian Division, 1942-1947. Eastbourne: Naval Millitary Press.
- Hatta, M. 2011, Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Jakarta: Buku Kompas
- H. 2002, Memoar Hario Kecik: Otobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit. Jakarta. Pustaka Utan Kayu.
- Wiliater Hutagalung. 2016, Autobiografi Letkol (Purn) dr. Wiliater Hutagalung, Putra Tapanuli Berjuang di Pulau Jawa, Yogyakarta: Matapadi Pressindo.