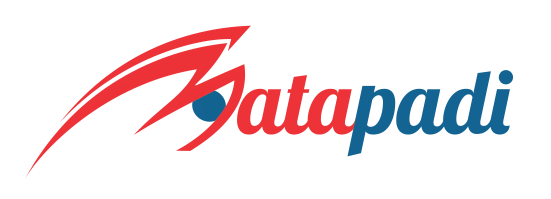Mengenang Dwi Tunggal Di Surabaya, Oktober 1945
April 2, 2020Sukarno Yang Ingkar : Aceh dan Daud Beurueh
April 6, 2020Natsir, Orde Baru dan Petisi 50
Foto tidak berkait langsung dengan postingan. Keterangan foto: Anwar Harjono (tengah), M. Natsir (kanan), Yunan Nasution (kiri). Sumber foto: repro dari lama republika.co.id
Sudah sejak awal berkuasa, Orde Baru muncul dengan kebijakan-kebijakan yang progresif, kontroversial sekaligus meninggalkan polemik yang berujung pada sikap resisten. Dalam beberapa hal, kebijakan yang dikeluarkan semakin menampakan kekhawatiran, bahwa kekuasaannya akan digoyah atau dirongrong. Sebuah pandangan yang paranoid.
Dalam dasawarsa pertama Orde Baru berkuasa, muncul berbagai macam aksi, mulai dari kritik hingga aksi demontrasi; beberapa di antaranya disertai dengan tindakan kekerasan. Sebut saja dalam Peristiwa Malari, Gerakan Mahasiswa Bandung 1977-1978 atau rangkaian aksi mahasiswa lainnya.
Dalam pandangan pemerintahan Orde Baru, kritik akan dianggap sebagai upaya awal untuk pelengseran kekuasaan. Sedemikian itu kekhawatiran yang bisa terbaca. Orde Baru begitu gelisah ketika muncul suara-suara dari rakyatnya. Oleh karenanya, kritik akan selalu dibungkam. Jika perlu dihilangkan.
Demokrasi, sejatinya adalah memberikan ruang dan jalan aspirasi. Jika itu terhalang, maka laksana air bah yang meluap dari bibir-bibir sungai, membludak dan menerjang apa saja yang menjadi penghalang.
Dalam sebuah pidato di depan Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru, Riau, tanggal 27 Maret 1980, Presiden Suharto berbicara tentang Asas Tunggal Pancasila. Dalam pidatonya itu, Presiden menyampaikan bahwa Pancasila pada masa lalu telah dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik.
Sebelumnya pada tahun 1978, pemerintah Orde Baru mengeluarkan instruksi yang mengharuskan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di departemen-departemen pemerintahan, sekolah-sekolah, tempat-tempat kerja, dll.
Setelah pidatonya dalam Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru, sekitar dua pekan kemudian, tepatnya tanggal 16 April 1980, dalam peringatan HUT Kopassandha di Markas Kopassandha (Kopassus) Cijantung, Presiden Suharto kembali menegaskan dengan menyampaikan:
“… Lebih baik kami culik satu dari dua pertiga anggota MPR yang akan melakukan perubahan UUD 1945 agar tidak terjadi kuorum“. Lebih lanjut, Presiden Suharto dengan penuh percaya diri menunjukkan sikap otokratnya, dengan menyatakan, “… Yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila“.
Pidato Suharto ini kemudian membuat gundah banyak pihak, termasuk Natsir yang ketika itu sedang memimpin sidang yang membahas konflik etnis Yunani dan Turki di Siprus pada bulan April 1980.
Natsir, secara tiba-tiba jatuh sakit. Namun dokter yang memeriksanya tak menemukan gejala yang mencurigakan. Rupanya Natsir memikirkan dinamika politik yang tengah terjadi di dalam negeri. “Pikiran saya terganggu oleh pidato Suharto“, kata Natsir.
Pidato itu akhirnya juga memunculkan banyak reaksi dari beberapa kalangan. Sekelompok jenderal purnawirawan yang gundah dengan pidato Presiden Suharto itu kemudian membentuk Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) Angkatan Darat. Sebelumnya telah dibentuk juga forum Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB) yang digawangi Nasution dan Hatta pada 1978.
Beberapa tokoh jenderal purnawirawan ini antara lain, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Nasution; mantan Kapolri, Hoegeng Imam Santoso; mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin dan masih banyak lagi.
Mereka kemudian mengadakan pertemuan di Gedung Granadi, di kawasan Semanggi, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung tanggal 5 Mei 1980 itu mengerucut pada simpulan bahwa, Presiden Suharto perlu ditanya soal pidatonya itu.
Simpulan dalam pertemuan itu menghasilkan dengan apa yang kelak disebut sebagai Petisi 50. Yang berupa dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Suharto terhadap lawan-lawan politiknya.
Petisi ini merupakan “Ungkapan Keprihatinan” yang ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, termasuk tokoh di luar jenderal purnawirawan, antara lain mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir, juga beberapa tokoh lainnya.
Dalam petisi ini dinyatakan bahwa Presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila; bahwa Suharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila; Soeharto menggunakan Pancasila “sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya”; Soeharto menyetujui tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer; sumpah prajurit diletakkan di atas konstitusi; dan bahwa prajurit dianjurkan untuk “memilih teman dan lawan berdasarkan semata-mata pada pertimbangan Soeharto”.
A.M. Fatwa dan beberapa tokoh aktivis lainnya yang bergerilya untuk mencari dukungan terhadap enam butir “Ungkapan Keprihatinan”. Setelahnya, Petisi ini akan disampaikan kepada Ketua DPR yang saat itu dijabat oleh Daryatmo. Natsir kemudian didaulat untuk menyampaikannya kepada ketua DPR itu.
DPR dipilih sebagai instrumen menyampaikan pendapat karena para tokoh ini memang menghendaki bahwa, apa yang mereka kemukakan adalah sesuai dengan konstitusi. Dalam arti, bahwa tindakan mereka sangat konstitusional.
Petisi ini dibacakan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 13 Mei 1980 dengan maksud untuk meyakinkan para wakil rakyat agar meminta penjelasan dari Presiden tentang apa maksud yang sesungguhnya dengan kedua pidatonya itu.
Dalam pertemuan itu Natsir menyampaikan, “… Bagi seorang Presiden, pidato lisan atau tertulis sama nilainya di mata masyarakat. Kami ingin bertanya apa maksud dari pidato itu“.
Presiden Suharto yang mengetahui kabar ini, bereaksi keras menanggapi pernyataan itu. Pernyataan yang diwakili Natsir itu dijawabnya melalui surat kepada DPR tertanggal 1 Juni 1980.
Sudomo, yang ketika menjabat sebagai Pangkobkamtib, menganggap pernyataan dalam Petisi 50 itu telah menyinggung pemerintah karena menyiratkan usul pergantian pemimpin nasional.
Singkatnya, Natsir kemudian dicekal, termasuk beberapa tokoh lain di dalamnya. Bagi Natsir, perlakuan buruk pemerintah bukan kali ini saja. Natsir diketahui juga pernah bersilang pendapat dengan Sukarno soal gagasan Nasakom dan beberapa hal lainnya.
Selanjutnya, keberadaan kelompok Petisi 50 ini dianggap sebagai musuh utama pemerintahan Suharto. Selain cekal, para tokoh yang terlibat di dalamnya juga mengalami semacam boikot, terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi mereka.
Tersiar kabar bahwa Suharto juga berkeinginan mengirim mereka ke Pulau Buru, namun konon upaya ini bisa digagalkan oleh Jenderal M. Jusuf, Panglima ABRI yang menentang tentara berpolitik.
Meski dicekal dan rumah-rumah para tokoh yang terlibat dalam Petisi 50 itu juga diawasi intelijen, mereka lantas tak surut. Mereka rutin melakukan Pertemuan Selasa sore di kediaman Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta yang juga motor dari kelompok ini.
“Meski tak rutin, Pak Natsir sering datang,” kata A.M Fatwa. “Dia juga menjadi donatur Petisi.”
Tak terasa, pertemuan setiap Selasa itu telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Mereka sering mengadakan diskusi dan bertukar gagasan tentang soal-soal kenegaraan atau membahas situasi politik. Outputnya, secara rutin pula, setiap 17 Agustus pada peringatan Kemerdekaan, Petisi mengeluarkan maklumat atau memorandum yang isinya mengkritik kebijakan-kebijakan Orde Baru.
Satu warisan Natsir yang terkenal yang muncul ketika diskusi dalam Petisi 50 berlangsung panas dan runcing,
“Kita sepakat untuk tidak sepakat”
Bahan bacaan:
- Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim, Indonesia di Persimpangan Jalan.
- https://majalah.tempo.co/read/memoar/210/kisah-seputar-petisi-50?
- Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan.
- Bresnan, John Managing Indonesia: The Modern Political Economy, New York: Columbia University, 1993 h. 207.
- Cited in Friend, T. (2003). Indonesian Destinies. Harvard University Press.