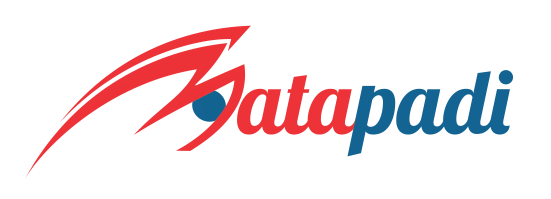Nyala Redup Sang Penyulut Soenting Melajoe
January 4, 2022Kisah Klasik Istri Mohammad Hatta: Dari Mas Kawin Buku Sampai Mesin Jahit
January 26, 2022Agresi Militer, Salah Perhitungan Belanda, dan Watak Sri Sultan IX

Pasukan Belanda pada Agresi Militer Belanda ke-II. Sumber: www.nationaalarchief.nl
Sejak serbuan Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948 sampai Januari 1949, suasana mencekam terjadi. Peristiwa demi peristiwa berkecamuk. Pimpinan tertinggi Republik Indonesia diasingkan ke tempat jauh. Ketika Panglima Besar Jenderal Soedirman (1912/1916-1950) memimpin gerilya, pejabat republikein yang masih di Yogyakarta ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Serangan Belanda bersandi Operatie Kraai bukan berarti tak pernah diperkirakan. Dalam buku Mempertahankan Republik: Doorstoot Naar Djogja 1948 (Matapadi Pressindo, 2020: 13-17), Wawan K. Joehanda memaparkan analisa dan pendapat Letkol Wiliater Hutagalung. Perwira teritorial yang bertugas membangun jaringan gerilya di wilayah Divisi II dan Divisi III itu menyampaikan analisa kepada Kolonel Bambang Soegeng dan Letkol Sarbini dalam sebuah rapat.
“Saya yakin bahwa Belanda mengetahui keadaan kita di seluruh Jawa dan Sumatera lebih mendetail daripada kita sendiri,” ujar Wiliater Hutagalung. Dalam analisanya, ia memperkirakan Belanda berangkat pagi buta dari Semarang mengangkut pasukan payung dan akan menguasai Maguwo dalam waktu setengah jam. Ibu kota Republik Indonesia akan dikuasai tak lebih dari satu hari.
Analisa Wiliater Hutagalung ini termaktub juga dalam buku karya Batara Hutagalung berjudul Autobiografi Letkol TNI (Purn) dr. Wiliater Hutagalung, Putra Tapanuli Berjuang di Pulau Jawa; Penyusun “Grand Design” Serangan Spektakuler Terhadap Yogyakarta 1 Maret 1949 (Matapadi Pressindo, 2016). Tak hanya Wiliater Hutagung, Abdul Haris Nasution (1918-2000) memiliki analisa tak jauh beda.
Saat berada di Jawa Timur pada 17-19 Desember 1948, A.H. Nasution selaku Panglima Tentara & Teritorium Djawa/Markas Besar Komando Djawa (PTTD/MBKD) menghadiri peresmian Divisi I/Brawijaya di Kediri. Saat acara, ia bersuara, “Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang lagi, mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa…”
Soal Belanda akan melancarkan Agresi Militer II, Panglima Besar Jenderal Soedirman sebenarnya juga gelisah di Rumah Sakit Panti Rapih. Ia yang masih dalam pemulihan setelah operasi paru-paru memaksa pulang. Hatinya ingin segera terjun berjuang. Sebelum Belanda melancarkan Operatie Kraai, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah merumuskan siasat gerilya yang populer dengan Perintah Siasat No. 1. Tentu, ada firasat cemerlang seorang Soedirman yang memaksa pulang sebelum 19 Desember 1948.
Menarik membaca artikel George McTurnan Kahin (1918-2000) berjudul “Sultan dan Belanda”. Ia menuliskan, “…selama bulan-bulan sebelum gerakan militer besar-besaran yang mereka lancarkan tanggal 19 Desember 1948, slogan tentara Belanda adalah: ‘Terus ke Yogya untuk membebaskan Sultan (on to Yogya to free the Sultan)’.”
Menurut sejarawan asal Amerika Serikat yang fokus pada studi Asia Tenggara itu, Belanda melakukan kesalahan fundamental mengenai watak Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Secara faktual, Belanda memang terlalu percaya diri. Wilayah Republik Indonesia yang hanya—meminjam istilah Soedirman–selebar daun kelor seolah-olah akan bisa dikuasai dengan mengerahkan seluruh peralatan perang dan pasukan dari darat dan udara.
Bukan hanya kekeliruan membaca watak Sri Sultan IX, Belanda pun salah menilai kekuatan TNI dan rakyat. Kendati wilayah Jawa hanya tinggal 1/3 dan wilayah Sumatera hanya 1/5, namun Sumatera Barat dan Aceh bukanlah nyamuk yang mudah ditepuk. Menangkap Sukarno-Mohammad Hatta dianggap urusan bakal mudah, namun Belanda tak memperhitungkan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989).
Soal watak Sri Sultan IX, menarik jika membaca kembali artikel Goerge McTurnan Kahin berjudul Sultan dan Belanda yang tertuang dalam buku Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982, 2011: 188-195). Penulis akan mengutip sebagian dari tulisan George McTurnan Kahin tersebut.
George McTurnan Kahin menulis:
“Ketika Belanda tiba di Yogya pada tanggal 19 Desember 1948, tak ada sambutan dari Sultan. Ia memasang perintang di pintu gerbang Keraton dan menolak menerima kedatangan panglima militer Belanda setempat, Jenderal Meyer, atau para pejabat sipil Belanda. Kemudian ketika panglima pasukan Belanda, Letnan Jenderal Spoor, secara nekat mengendarai tank Stuart menuju pintu gerbang Keraton dan akan mengancam akan menerobos masuk, Sultan menyarankan agar ia turun dari tanknya dan jalan kaki ke dalam. Spoor ingin membicarakan ‘kerja sama’ dan apa yang akan diberikan Belanda kepada Sultan sebagai imbalan. Akan tetapi, satu-satunya masalah yang ingin dibicarakan Sultan adalah penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta, dan pada akhir pertemuan selama sepuluh menit itu ia mengisyaratkan dengan dingin bahwa pembicaraan itu telah selesai, lalu meninggalkan ruangan.”
George McTurnan Kahin melanjutkan:
“Ketika saya kembali ke Yogya untuk kunjungan pada minggu kedua bulan Januari sebagai koresponden surat kabar (setelah ditahan Belanda sebagai sarjana yang baru lulus dan dipaksa meninggalkan Indonesia pada tanggal 19 Desember), saya terkejut akan ketidakberdayaan para pejabat Belanda dalam menghadapi politik nonkooperasi Sultan. Kepala urusan ekonomi Belanda di sana, Dr. B.J. Mulder, mengatakan kepada saya bahwa dari kurang 10.000 pegawai sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta tak lebih dari 150 yang bekerja untuk pemerintahan pendudukan Belanda. Dan ia cukup berterus terang untuk mengakui bahwa dia percaya segelintir orang ini berbuat demikian hanyalah karena Sultan memerintahkan mereka sehingga penduduk sipil tak menanggung penderitaan yang tak perlu. (Para pegawai yang bekerja pada Belanda ini adalah di bagian perairan, pusat tenaga listrik, rumah sakit, dan jawatan kebersihan). Dihadapkan pada situasi ini, Belanda menyadari bahwa meskipun mereka bisa mempertahankan kekuasaan militer di daerah itu, keadaan mereka tak akan tertahankan, kecuali jika bisa membujuk sejumlah besar pegawai sipil Indonesia untuk bekerja sama dengan mereka. Lebih daripada sebelumnya, mereka melihat Sultan sebagai kuncinya. Apabila mereka bisa merebut dukungannya, mereka percaya bahwa cukup banyak pegawai sipil dan penduduk setempat lainnya yang akan meninggalkan sikap nonkooperasi untuk menyukseskan pendudukan Belanda.”
Dalam tulisan berbahasa Inggris berjudul asli “The Sultan and the Dutch” yang diterjemahkan ini, George McTurnan Kahin menulis:
“Oleh karena itu, Belanda berkesimpulan bahwa mereka harus mengajukan tawaran kepada Sultan yang demikian menarik sehingga ia akan bersedia bekerja dengan mereka. Pada awal Februari, melalui kakaknya (yang diperintahkan ya bertugas sebagai sebagai penyangga (buffer) dengan wewenang mendengarkan, tetapi tidak menanggapi pesan Belanda yang bagaimana pun), para pejabat Belanda mengajukan tawaran yang sama yang oleh Jepang pernah diajukan, tetapi tidak membawa hasil. Yaitu mendirikan kembali satu daerah yang sama dengan Kesultanan Mataram yang lama, meliputi Yogyakarta, Surakarta, Kedu, Banyumas, dan Madiun dengan Sultan sebagai Wali Negaranya. Karena kakak Sultan tidak memberikan tanggapan, Belanda berkesimpulan bahwa tawaran itu tidak cukup besar dan bahwa Sultan bertahan agar mendapat yang lebih banyak. Dengan demikian, keesokan harinya mereka memperluas wilayah negara yang akan dikepalai Sultan. Pada daerah “Mataram” itu mereka tambahkan seluruh sisa bagian Jawa Tengah dan seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Madura. Karena kakak Sultan tetap berdiam diri lagi, maka pada hari ketiga para pejabat Belanda mengajukan apa yang mereka katakan usul terakhir untuk merebut kerja sama dari Sultan, syarat-syarat terbaik yang menurut mereka bisa diajukan–semua daerah yang sudah disebutkan berikut janji tentang sejumlah besar saham di KPM, perusahaan pelayaran Belanda, dan di Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. Sultan segera menolak tawaran ini, dan Belanda akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka sungguh-sungguh telah salah menilai Sultan Hamengku Buwono IX.”
Agresi Militer Belanda Kedua memang kegilaan mendadak. Belanda salah perhitungan terhadap kekuatan Republik Indonesia, salah pula membujuk rayu Sri Sultan IX. Wallahu a’lam. (Hendra Sugiantoro).